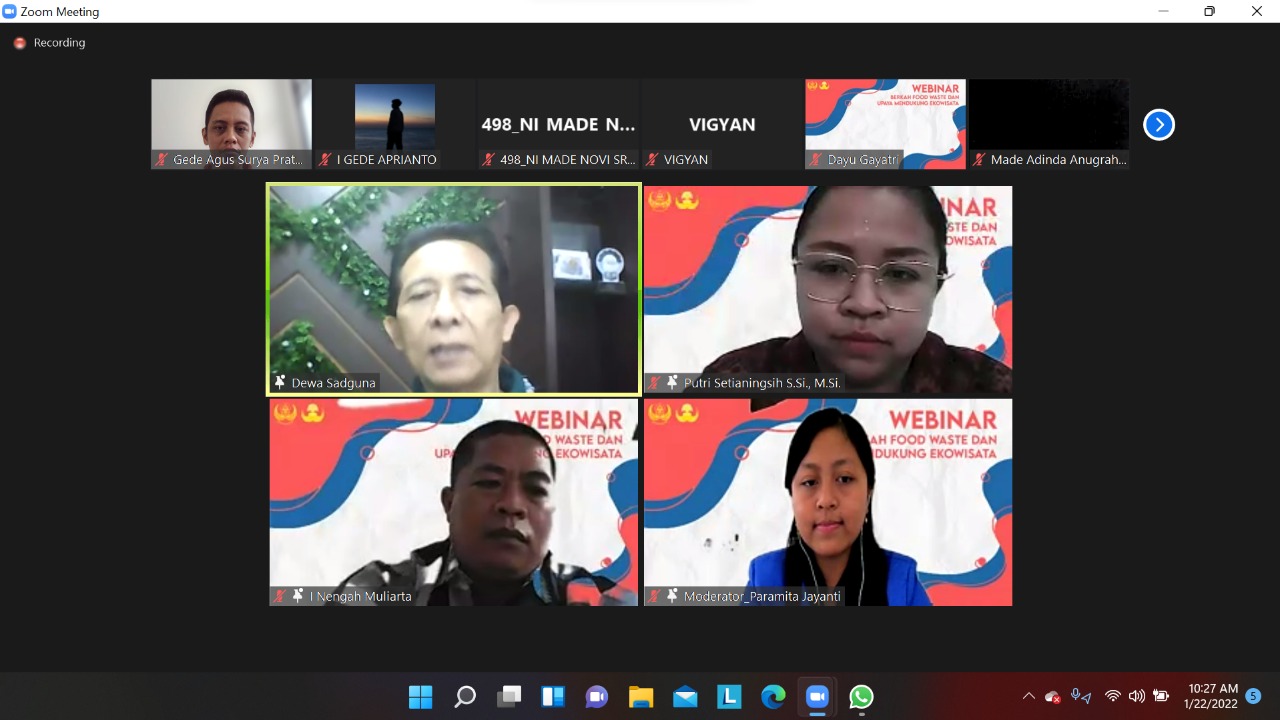Muliarta mengungkapkan, era digital saat ini menyebabkan pola pembelian makanan memberi kontribusi terhadap jumlah limbah makanan yang dihasilkan. Semakin besar rata-rata pengeluaran untuk membeli bahan makanan pada satu waktu, semakin besar kemungkinan menghasilkan lebih banyak limbah makanan.
Limbah makanan tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan, tetapi juga memainkan peran utama dalam menciptakan kerugian ekonomi dan masalah sosial yang tidak perlu.
Dampak ekonomi yang besar dari membuang makanan mempengaruhi semua individu dan organisasi yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.
Apalagi fenomena di negara maju, makanan dipandang sebagai komoditas sekali pakai. Dampaknya sekitar sepertiga atau setengah dari semua makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia secara global diperkirakan akan terbuang percuma.
“Contoh kasus dalam sebuah penelitian tahun 2011 di Inggris, kontribusi terbesar untuk limbah makanan berasal dari rumah sebesar 8,3 juta ton per tahun, merugikan konsumen sebesar £12 miliar dan menyumbang 3% dari emisi gas rumah kaca Inggris” jelasnya.
Menurut Muliarta, praktek buruk pembuangan limbah makanan berdampak pada lingkungan berupa emisi gas rumah kaca, lindi, dan bau. Tumpukan limbah makanan akan menghasilkan gas metana yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada karbon dioksida dalam 100 tahun.
“Umumnya alasan rumah tangga tidak melakukan pemilahan sampah adalah terlalu malas, memiliki kesenjangan pengetahuan dan kurangnya fasilitas. Ini masalah klasik” katanya.
Muliarta menyebutkan frekuensi makan berpengaruh cukup signifikan terhadap produksi limbah makanan. Dalam survei di kawasan Saridewi, Denpasar Utara yang telah menerapkan konsep zero waste sejak tahun 2020 terungkap bahwa 76,40% warga Saridewi memiliki frekuensi makan 3-4 kali dalam sehari.